Dewasa ini, jagat media sosial Indonesia diramaikan oleh kemunculan akun-akun bertajuk kampus cantik. Mulai dari @uicantikid, @itscantik, dan berbagai akun serupa yang mengekspos sejumlah potret mahasiswi dari universitas tertentu yang dianggap memiliki paras cantik atau sesuai dengan standar kecantikan khusus. Tidak hanya menampilkan foto, postingan tersebut juga dilengkapi dengan informasi berupa identitas mahasiswi yang bersangkutan, seperti nama, program studi, dan angkatan.
Sekilas, kehadirannya tampak sebagai bentuk apresiasi atau promosi citra positif kampus. Tetapi jika ditelisik lebih jauh, fenomena ini tidak dapat dipersepsikan sesederhana itu. Tren yang sempat booming di Instagram kini juga telah menjalar ke platform lain seperti TikTok yang dikemas dalam bentuk video jedag-jedug agar lebih memancing atensi.
Namun dibalik popularitasnya, tren ini justru menuai beberapa dampak negatif yang justru merugikan sebagian pihak. Artikel dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mencatat, banyak mahasiswi merasa foto mereka diunggah tanpa izin dan menjadi sasaran komentar bernada seksual. Sementara Universitas Airlangga menilai, fenomena ini merupakan bentuk “kekerasan kultural” karena menempatkan perempuan sebagai objek visual semata. Tidak hanya itu, kajian dari FISIP UI bahkan menyebutnya sebagai bentuk pendisiplinan tubuh perempuan, di mana mahasiswi didorong untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan tertentu agar diterima di ruang sosial kampus.
Sebenarnya tidak masalah jika mahasiswa ingin mengikuti tren atau sekadar FOMO (Fear of Missing Out) di media sosial. Pasalnya, dunia digital memang bergerak cepat, sehingga setiap orang punya cara tersendiri untuk berekspresi. Namun, yang sering terabaikan adalah konsekuensi yang ditimbulkan akibat mengikuti suatu tren tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kemunculan tren “kampus cantik” ini mungkin tampak sepele, tetapi hal tersebut pada dasarnya berpotensi menimbulkan lebih banyak dampak negatif jika dilihat dari aspek sosialnya. Seperti membentuk standar kecantikan baru yang sempit, menormalisasi penilaian berdasarkan fisik, dan menekan mereka yang tidak sesuai dengan penampilan atau citra yang sedang populer.
Kemunculan akun @fineshyt.ulm pada platform TikTok menjadi indikasi yang menunjukkan tren ini juga telah sampai ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Serupa dengan fenomena yang terjadi pada akun “kampus cantik” lain, akun ini juga menampilkan sejumlah potret mahasiswi dari berbagai fakultas. Melalui kolom komentarnya, terlihat bagaimana publik turut berperan dalam menentukan standar kecantikan baru.
Komentar seperti “Nah Fineshyt tuh vibes kaya ini” sekilas tampak biasa, namun jika dimaknai lebih dalam, pernyataan tersebut sebenarnya mengandung unsur perbandingan yang membentuk hierarki visual. Artinya, ada wajah yang dianggap “ideal,” sementara yang lain dianggap tidak sesuai dengan vibe yang diinginkan.
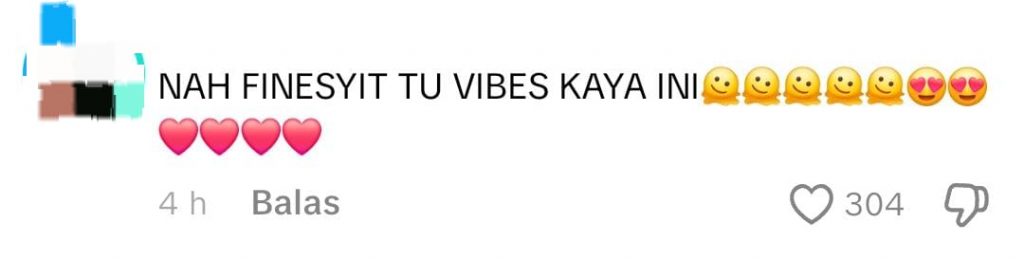
Menariknya terdapat ketidakseimbangan antar fakultas jika dilihat dari wajah-wajah yang diunggah pada akun tersebut. Fakultas Hukum, FISIP, dan FEB tampak lebih sering muncul dibanding fakultas lain. Pola seperti ini akan membentuk kesan yang memperlihatkan adanya klaster kecantikan yang dibedakan dari asal fakultas. Artinya, akan muncul anggapan yang menunjukkan fakultas tertentu identik dengan paras menawan, sementara fakultas lain tidak menjadi sorotan. Standar semacam ini bukan hanya mempersempit makna kecantikan, tapi juga memperkuat bias sosial di lingkungan akademik.
Padahal kecantikan seharusnya bersifat relatif, cair, dan tidak dapat diukur dengan likes maupun vibe . Namun di ruang digital, standar ini justru dibakukan oleh komentar dan algoritma. Akun seperti @fineshyt.ulm kemudian menjadi cermin bagaimana media sosial membentuk budaya perbandingan dan validasi visual di kalangan mahasiswa.
Lucunya di ruang akademik yang penuh teori kritis, justru algoritma yang paling berkuasa. Ia menentukan siapa yang patut dipuji, siapa yang hanya lewat di For You Page. Dan kita, entah sadar atau tidak, ikut menekan tombol suka, ikut menilai, ikut menormalisasi standar yang kita tahu tak pernah benar-benar adil.
Penulis: Wiri
Penyunting: Nada, Andika




